
TIGA tahun sudah program sertifikasi guru dijalankan. Profesionalitas sekaligus kesejahteraan para ”pahlawan tanpa tanda jasa” diharapkan terdongkrak dengan program itu. Namun alih-alih menjawab dua persoalan mendasar keguruan, sertifikasi justru memicu persoalan baru. Berikut perbincangan dengan Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo MSi, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang
menjadi penyelenggara program itu.
Banyak guru resah gara-gara ber¬edar kabar Forum Rektor LPTK akan memboikot, bahkan hendak menghentikan sertifikasi guru. Bagaimana sebenarnya?
Ini perlu diluruskan. Jangan sampai kabar yang belum jelas kebenarannya berdampak luas, bahkan bereskalasi. Tak ada kata memboikot. Di dalam pertemuan Forum Rektor LPTK beberapa wak¬tu lalu di Gorontalo, 12 LPTK yang merupakan perguruan tinggi eks-IKIP meminta ada kejelasan pedoman sertifikasi. Sebab, selama ini muncul anggap¬an penyelenggaraan sertifikasi diadakan oleh perguruan tinggi. Itu salah alamat. Perguruan tinggi ditugasi sebagai penyelenggara.
Memang ada dinamika, ada sesuatu yang menimbulkan perbedaan tafsir. Inilah yang harus dijelaskan. Ada perbedaan tafsir atas pedoman penyelenggaraan Karena itu, kami meminta kejelasan pedoman pada 2009 ini agar penyelenggaraan sertifikasi 2010 berjalan lancar dan clear.
Kabarnya Persatuan Guru Republik INdonesa (PGRI) mengancam akan melakukan gerakan organisasi jika Fo¬rum Rektor LPTK benar-benar meng¬hentikan proses sertifikasi?
Saya setuju. Memang harus demikian. PGRI sebagai wadah para guru sudah semestinya bergerak ketika yang diwa¬dahi tidak mendapatkan yang seharusnya didapatkan. Meskipun demikian, tentu mereka tidak bisa menekan siapa pun, termasuk LPTK. Justru yang perlu ditekan adalah pemerintah. Para rektor juga tahu persis, batas-batas mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Tiga tahun berjalan, tak sedikit yang beranggapan sertifikasi tak mampu juga mendongkrak profesionalitas guru. Pendapat Anda?
Saya tidak menampik anggapan itu. Perguruan tinggi menyelenggarakan sertifikasi guru atas dasar portofolio, tapi tidak diketahui guru bisa mendapat portofolio. Bagaimana cara mendapatkannya pun tidak diketahui.
Guru dikatakan profesional jika telah memenuhi syarat. Guru profesional itu se¬ha¬rusnya memiliki kemampuan ke¬pri¬ba¬dian, kemampuan sosial, kemampuan pro¬fesional, dan kemampuan paedagogis.
Kami sepakat dengan pendapat ma¬sya¬rakat, sertifikasi guru belum sepenuhnya berjalan baik. Namun tentu kita masih memiliki harapan, dengan sertifikat di tangan seharusnya setiap guru pantas menjadi teladan bagi dirinya dan menjadi contoh bagi semua.
Ada yang beranggapan penilaian sertifikasi dengan teknik portofolio hanya membuat guru mengejar sertifikat, bahkan mendorong para guru membuat sertifikat asli tapi palsu.
Konon cerita itu terjadi. Namun persoalannya tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Orang dikatakan profesional kok hanya karena mengum¬pul¬kan sertifikat, apalagi sertifikat itu diperoleh dengan cara yang tidak semestinya. Misalnya mengikuti seminar atau pelatihan dengan hanya membayar dan titip nama untuk mendapatkan sertifikat.
Itu merupakan upaya tidak jujur, ha¬nya mencari keuntungan diri, sekaligus mengabaikan kepatutan, nilai-nilai moral, dan akademik. Padahal, semangat sertifikasi pada mulanya adalah untuk membangun guru yang profesional. Tapi lepas dari persoalan teknis macam begitu, ini sangat terkait dengan sistem dan budaya.
Anda melihat dampak yang lebih buruk dalam pelaksanaan sertifikasi, baik bagi guru maupun siswa, dan pendidikan pada umumnya?
Dengan sertifikasi, seolah-olah seluruh perhatian dan waktu habis sudah untuk menggenapi portofolio. Akibat¬nya, tugas utama guru untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswanya seringkali terkesampingkan. Ini ironis sekali. Tidak boleh terjadi dan harus se¬gera dibenahi.
Program sertifikasi juga telah ikut memicu kejadian-kejadian ekstrem yang menimbulkan keirian. Misalnya muncul kecemburuan antarguru di sebuah sekolah. Sertifikat seolah-olah hanya menjadi alat untuk menjustifikasi seseorang mendapatkan tunjangan.
Memang proses sertifikasi belum se¬pe¬nuhnya baik. Ada guru yang sudah ter¬sertifikasi dan memang sudah sepantasnya mendapatkan sertifikat, tetapi tidak kurang pula guru yang sebetulnya belum pantas mendapatkan justru sudah memperolehnya.
Bagaimana sebenarnya proses sertifikasi guru yang lebih akuntabel?
Lebih baik dengan kegiatan pelatihan, bukan portofolio. Perlu ada pelatihan untuk mengukur standar kemampuan guru. Dengan pelatihan, mereka bisa saling asih, asah, dan asuh. Ada pertukaran pengalaman. Ini sangat berbeda dari portofolio.
Berdasarkan pengakuan sejumlah guru, meskipun pada awalnya merasa enggan mengikuti, setelah menga¬laminya mereka justru merasa senang bisa mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Dengan pelatihan, barulah guru benar-benar mendapatkan sesuatu yang selama ini belum dimiliki sehingga predikat profesional layak disandangnya.
Di sisi lain, untuk memenuhi akun¬tabilitas publik, di tempat kami (Unnes) nilai setiap guru yang mengikuti sertifikasi bisa diakses dengan bebas melalui internet. Siapa pun bisa melakukan konfirmasi atas nilai yang didapatkan.
Tak sedikit guru yang telah tersertifikasi, tapi belum juga memperoleh tunjangan sebagaimana yang dijanjikan. Akar persoalannya di mana?
Menurut informasi yang saya terima, anggaran dana sebenarnya sudah tersedia, ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Namun persoalannya, tidak serta merta setelah lulus sertifikasi seseorang bisa langsung mendapatkan tunjangan. Ada prosesnya.
Persoalan yang selama ini menghambat pencairan tunjangan adalah masih adanya proses administrasi yang belum dilaksanakan dengan baik.
Bagaimana mengatasinya?
Semestinya Dinas Pendidikan, baik di tingkat kota maupun kabupaten proaktif membantu dan mengawal guru dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai waktu yang dimiliki guru habis hanya mengurusi persoalan sertifikasi. Guru semestinya memberikan layanan kepada anak didiknya dengan baik, sedangkan kepentingan guru dilayani Dinas Pendidikan.
Angka ketidaklulusan begitu tinggi dalam kegiatan sertifikasi. Berdasarkan data 2007, guru yang lulus sertifikasi 30% dan 2008 yang lulus 50%. Ba¬gaimana ini?
Tahun 2007 merupakan awal penyelenggaraan sertifikasi. Wajarlah bila masih begitu banyak yang belum lulus, karena baik guru maupun dosen belum memiliki pengalaman dan belum memahami proses sertifikasi yang sebenarnya.
Bagaimana dengan sertifikasi dosen? Apakah juga ”bernasib” sama dengan sertifikasi guru?
Dalam sertifikasi dosen, jumlahnya sedikit sehingga relatif lancar. Di perguruan tinggi, anggaran dana sudah masuk DIPA. Tidak ada masalah. Tiap bulan otomatis masuk ke gaji para dosen.
Sertifikasi dosen juga ditangani oleh perguruan tinggi. Misalnya dosen Unnes disertifikasi dosen-dosen perguruan tinggi lain, sedangkan Unnes menjadi asesor di perguruan tinggi lain, seperti ITB dan UI. Segala kebijakan yang mengatur hal ini adalah pusat. Kami tinggal mengirim sesuai dengan kouta.
Sistemnya juga sama dan masih ada celah-celah, tapi sudah agak bagus di¬bandingkan dengan sertifikasi guru. Sistem yang digunakan pun sama, yaitu de¬ngan portofolio. Bedanya, jika ada dosen yang tidak lulus, bisa mengikuti sertifikasi dua tahun kemudian.
Proses sertifikasi guru dan dosen ditargetkan selesai 2015. Bisakah target itu tercapai?
Yang mendesak sebenarnya bukan selesai atau tidak pada tahun itu, me¬lain¬kan perlunya evaluasi tiap tahun, terutama sistemnya. Jangan seolah-olah ke¬giatan ini target semata tetapi hilang fi¬losofinya, sekalipun kesejahteraan para guru meningkat.
Semestinya targetnya adalah adanya peningkatan kualitas, karena sertifikasi dilaksanakan berangkat dari kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan. (35)
(Dikutip dari hasil wawancara oleh Suara Merdeka , 22 Nopember 2009)
Vision
Have graduates that professional on the work and bussines and they also can continue their education to the college
Mission
Give education service to students and people thraugh nasional standad education and training that have orientation technically, bussines and academic on expertise program
Important Information
Masyarakat Karimunjawa dan sekitarnya yang memmerlukan ketrampilan / kursus singkat aplikasi komputer dan pengolahan perikanan silahkan daftar di Career Center SMK Negeri 1 Karimunjawa
Vocational Program
1. Agribisnis Rumput Laut
2. Teknologi Hasil Pertanian (Pengolahan Hasil Perikanan)
3. Agribisnis Perikanan
2. Teknologi Hasil Pertanian (Pengolahan Hasil Perikanan)
3. Agribisnis Perikanan
Informasi Tes Semester
1. Tes Semester Genap dilaksanakan mulai tanggal 4 s/d 12 Juni 2010
2. Tes Perbaikan dilaksanakan mulai 14 s/d 16 Juni 2010
3. Pembagian Buku Rapor tanggal 19 Juni 2010
4. Libur akhir semester genap mulai tanggal 21 Juni 2010 s/d 10 Juli 2010
5. Masuk KBM 2010/2011 mulai Senin, 12 Juli 2010
2. Tes Perbaikan dilaksanakan mulai 14 s/d 16 Juni 2010
3. Pembagian Buku Rapor tanggal 19 Juni 2010
4. Libur akhir semester genap mulai tanggal 21 Juni 2010 s/d 10 Juli 2010
5. Masuk KBM 2010/2011 mulai Senin, 12 Juli 2010
Ayo sholat dulu
RAHASIA BISNIS INTERNET
Clock
Archives
Promotion
Bagi wisatawan asing atau lokal yang memerlukan sewa kapal dan perlengkapan selam, silahkan hub SMK Negeri 1 Karimunjawa
Contact Person :
1. Bp. Himawan (081325052395)
2. Bp. Anton (081392290304)
Contact Person :
1. Bp. Himawan (081325052395)
2. Bp. Anton (081392290304)

Sertifikasi Guru Mesti Dibenahi
Jumat, 27 November 2009
Diposting oleh SMK Negeri 1 Karimunjawa di 19.44
Label: berita, guru, sertifikasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)





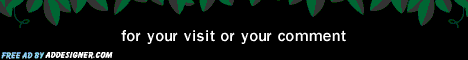









0 komentar:
Posting Komentar